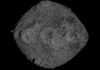Sepuluh tahun setelah dirilis, Star Wars: The Force Awakens (2015) berdiri sebagai momen penting: film yang bisa saja terjadi, namun ternyata tidak terjadi. Meskipun sambutan penggemar terhadap trilogi sekuelnya retak, kegembiraan awal seputar seri ketujuh itu nyata. Film ini menghidupkan kembali sebuah fenomena budaya, memadati bioskop dengan penonton yang bersemangat pada tahun 2015. Pertanyaannya bukan apakah film tersebut ditayangkan dengan hype, tapi mengapa janjinya pada akhirnya disia-siakan.
Cetak Biru Era Baru
Akuisisi Disney atas Star Wars pada tahun 2012 menimbulkan kontroversi. Namun, studio menunjuk J.J. Abrams – dikenal karena merevitalisasi waralaba seperti Star Trek – untuk memimpin reboot. Abrams memahami tantangannya: memuaskan basis penggemar yang sangat bersemangat sambil merencanakan masa depan.
The Force Awakens mencapai keseimbangan yang diperhitungkan. Itu menggemakan struktur A New Hope, sangat condong ke nostalgia sambil memperkenalkan karakter baru. Seperti yang dikatakan oleh Abrams sendiri, tujuannya adalah “awal, tengah, dan akhir yang mandiri” yang masih mengisyaratkan kisah yang lebih besar. Film ini bukanlah sebuah terobosan baru, namun merupakan titik masuk kembali yang aman dan efektif bagi franchise tersebut.
Film ini memperkenalkan Rey (Daisy Ridley), Poe Dameron (Oscar Isaac), dan Finn (John Boyega) bersama ikon yang kembali seperti Han Solo (Harrison Ford) dan Leia Organa (Carrie Fisher). Luke Skywalker (Mark Hamill) tetap absen, membangun antisipasi akan kembalinya dia yang tak terelakkan.
Kebangkitan dan Kejatuhan Orde Pertama
Para penjahat juga sama pentingnya. Snoke (Andy Serkis) berperan sebagai pengganti Palpatine, sementara Kylo Ren (Adam Driver) mewujudkan warisan Darth Vader yang tersiksa. Pembunuhan mengejutkannya terhadap Han Solo menandakan bahwa pertaruhannya nyata, dan galaksi tidak kenal ampun.
Kesuksesan film ini tidak dapat disangkal: lebih dari $2 miliar di box office dan sebagian besar mendapat ulasan positif. The Force Awakens menjadi landasan bagi trilogi baru, namun yang terjadi selanjutnya mengungkap kelemahan fatal: kurangnya visi terpadu.
Keruntuhan Kreatif Sekuelnya
Masalahnya bukan pada film pertama; itulah yang terjadi selanjutnya. Lucasfilm melalui tiga sutradara – Abrams, Rian Johnson, dan akhirnya, lagi-lagi Abrams – masing-masing dengan pendekatan yang berbeda. Hal ini mematahkan narasinya, menyebabkan perubahan nada yang mengejutkan dan alur cerita yang terbengkalai.
The Last Jedi karya Rian Johnson membongkar landasan yang diletakkan oleh The Force Awakens. Film ini menumbangkan ekspektasi, memotong alur cerita yang sudah ada, dan mengasingkan sebagian dari basis penggemar. Bagian terakhir, The Rise of Skywalker, mencoba mengoreksi arah, namun malah terasa terburu-buru dan tidak koheren. Karakter-karakter kunci dikesampingkan, titik-titik plot dihubungkan kembali, dan keseluruhan cerita terasa terputus-putus.
Rencana awal untuk trilogi yang kohesif berubah menjadi serangkaian keputusan yang kontradiktif. Snoke meninggal tanpa penjelasan, garis keturunan Rey berubah drastis, dan alur penebusan Kylo Ren terasa tidak pantas. George Lucas sendiri menyuarakan kritik terhadap penanganan Disney terhadap franchise tersebut, menyoroti kurangnya arah yang jelas.
Peluang yang Terlewatkan
The Force Awakens bukanlah film yang sempurna, namun mewakili jalan ke depan yang jelas. Keberhasilannya membuktikan bahwa penonton menginginkan Star Wars kembali, dan formulanya menawarkan landasan yang stabil untuk seri berikutnya. Tragisnya adalah potensi ini ditinggalkan demi eksperimen yang terputus-putus. Film ini menjadi pengingat bahwa reboot yang paling menjanjikan pun bisa gagal ketika kepemimpinan kreatif melemah.
Kisah trilogi sekuelnya berfungsi sebagai sebuah kisah peringatan: sebuah waralaba dapat dibatalkan bukan karena ide-ide buruk, tetapi karena tidak adanya visi yang koheren. The Force mungkin kuat, tetapi ia pun tidak dapat menyelamatkan galaksi tanpa rencana.